ARTICLE AD BOX
Apakah Anda pernah mengalami homesick di rumah sendiri, seperti nostalgia pada alam nan indah, air nan jernih, gunung nan sejuk, alam nan terbuka, kembang nan warna warni, pohon nan rindang, dan semacam itu. Perasaan itu begitu dalam hingga menimbulkan keresahan placeless pada dekapan semesta nan damai.
Limitasi ruang, apalagi di tengah kepungan gedung, menyeret kita tertatih tatih mengumpulkan kepingan ingatan bakal bumi nan nyaman itu. Tetapi ingatan itu terus mengakumulasi, acapkali meletup dalam corak ketidakstabilan emosi, stress, dan impuls negatif lainnya nan membingungkan lantaran tidak diketahui persis karena musababnya.
Orang kota menerjemahkannya menjadi piknik, bertamasya ke alam, mudik ke kampung halaman, dan semacam itu. Namun, sungguh pun itu semua rutin dilakukan, apalagi jadi industri pariwisata masif hari ini, manusia saat ini tidak pernah luruh dari homesick semacam itu.
Glenn Albrecht menyebut jenis pengalaman seperti itu sebagai solastalgia. Terminologi itu digunakan Albrecht pada tahun 2003 dalam presentasinya di Konferensi Kesehatan Lingkungan (Ecohealth Conference) di Montreal Kanada. Istilah itu merupakan tesis dari refleksi Albrecht atas hubungan nan gamblang antara kerusakan lingkungan dan patologi psikis nan dialami masyarakat original di Australia akibat pertambangan batu bara.
Patologi terjadi lantaran goyahnya keseimbangan kosmos pada suatu komunitas, berikut individu-individu di dalamnya. Dalam teori-teori kesehatan dan lingkungan, manusia dan jagad hidupnya berkarakter interaktif. Dalam setiap pribadi dan organisasi terdapat keseimbangan nan terpelihara antara jagad tubuh (mikro kosmos) dan jagad semesta (makro kosmos) nan membentuk pengertian-pengertian relasional di antara keduanya sekaligus membentuk kesehatan suatu pribadi dan organisasi nan berkarakter holistik. Dengan kata lain, alam nan sehat bakal menyehatkan manusia. Sebaliknya, alam nan porak poranda juga bakal meluluhlantakkan kesehatan manusia.
Solastalgia merupakan campuran dari kata Latin solus dan kata Yunani algia. Solus artinya sendirian, sepi, kesunyian, terasing. Kata ini kemudian berkembang menjadi desolate, ialah hilangnya kenyamanan nan disertai kepedihan nan dalam, emosi kesenyapan akibat tercerabut dari kenyamanan.
Algia artinya rasa sakit, penderitaan, duka. Yakni tekanan emosional alias ketidakstabilan eksistensial nan diakibatkan oleh emosi tercerabut alias emosi terasing (solus). Albrecht mengalamatkan tekanan tersebut pada perubahan lingkungan nan disandingkan dengan nostalgia ekologis, sehingga menyulutkan stres emosial, ialah emosi tercerabut dari lingkungan.
Ketika dihubungkan dengan gambaran masa depan, ketidaknyamanan itu memupuk trauma eksistensial ialah kekhawatiran terhadap topangan alam nan terus tergerus dan lenyap, melahirkan kekhawatiran ekologis.
Pada tahun 2007, Albrecht mendalami istilah itu dalam situasi nan dihadapi suku Wonnarua and Awabakal di wilayah Upper Hunter New South Wales, Australia. Dua suku ini menyaksikan dan mengalami hilangnya alam nan mereka jiwai dari generasi ke generasi setelah sejumlah perusahaan pertambangan raksasa mengeruk wilayah leluhur mereka menjadi penambangan batu bara.
Situs sakral dan warisan kebudayaan nan mereka hayati sekonyong-konyong disulap jadi hamparan pengerukan nan kelam dan nyaris tidak dikenali lagi; suatu bumi alien nan menyedot mereka seperti mesin waktu dan dalam sekejap menjumpai realita nan kontras dengan peradaban mereka.
Tercerabut dari realita nan telah membentuk seluruh makna diri dan relasinya dengan dunia, menurut Albrecht meninmbulkan sindrom psikoteratik, ialah guncangan psikis akibat perubahan lingkungan. Ketika perubahan tersebut permanen, ingatan bakal tempat nan dulunya nyaman membayang-bayangi dan terus menjadi sandaran untuk mengukur masa depan.
Ironisnya, masa lampau itu tak pernah kembali. Inilah nan menjadi prinsip solastalgia, suatu nostalgia bakal alam nan memberi dekapan nyaman, alam tempat bersandar, alam nan memberi susu dan madu. Gerakan lingkungan dunia menyebutnya alam motherearth alias suku-suku Amerika Tengah menamainya pachamama. Solastalgia adalah kerinduan pada ibu nan lenyap nan terusir oleh deru mesin eskavator dan ledakan dinamit tambang. Orang Wonnarua and Awabakal memanggilnya pulang, tetapi sang Mama tak pernah kembali.
Pengalaman Wonnarua and Awabakal adalah tragedi dunia nan juga dialami oleh banyak wilayah lainnya. Banyak suku di Indonesia juga mengalami musnahnya bumi mereka dan alam nan memberi mereka makan akibat pemanfaatan mesin-mesin industri. Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Nusa Tenggara, mempunyai banyak inventarisasi narasi tragedi peralihan paksa dari bumi motherearth menjadi crazy earth.
Cerita ini lebih dalam pada masyarakat budaya dan organisasi lokal nan besar dan tumbuh berbareng alam. Mereka akhirnya terasing dari tanahnya sendiri. Sayangnya, belum banyak studi akademik nan mendalami akibat nan mereka alami dalam kaca mata kesehatan mental seperti kerja keras Albrecht dkk.
Di beberapa negara lain, mirip dengan studi Albrecht, para peneliti mulai menyelidiki pengalaman sensorik manusia dalam corak kekhawatiran ekologis. Tidak hanya pada masyarakat asli, kekhawatiran tersebut menguat pada masyarakat kota. Di Belanda, Venhof dkk (2025) menganalisa kekhawatiran ekologis menguat di kalangan usia 16-35 tahun, apalagi terakumulasi menjadi hilangnya kepercayaan pada otoritas nan kandas menjaga ikatan kolektif mereka pada alam nan mereka cintai. Studi lain di Amerika (Ballew et. al. 2024) juga menunjukkan meningkatnya aktivitas kolektif akibat pengalaman-pengalaman kekhawatiran lingkungan.
Indonesia juga sudah mulai melakukan identifikasi secara terpisah-pisah. Beberapa waktu lalu, sebuah diagnosa awal telah dimulai dari survei pandangan generasi muda terhadap rumor lingkungan. Lembaga Survei, Indikator, melakukan survei tahun 2021 pada 4020 responden dari dua golongan generasi usia ialah 17-26 dan 27-35 tahun.
Survei itu menemukan kekhawatiran nan signifikan dari generasi muda terhadap sejumlah masalah lingkungan (sangat kuatir dan agak kuatir). Mereka resah terhadap kerusakan lingkungan (84%), polusi (74%), dan perubahan suasana (70%). Semuanya ini menunjukkan bahwa kalangan generasi muda mulai memahami akibat masalah-masalah ini pada rumah masa depan mereka.
Solastalgia dan loneliness
Meskipun belum banyak dikupas, beberapa mahir meyakini solastalgia berkontribusi pada masalah kesenyapan eksistensial (loneliness) nan melanda kota-kota di seluruh dunia. Clayton Aldern dalam bukunya “The Weight of Nature: How a Changing Climate Changes Our Brains”, menulis kaitan kuat antara perubahan suasana dan keahlian otak serta persoalan mental. Pengaruh itu dapat meningkatkan ketegangan relasi sosial akibat gejolak mental nan membingungkan tidak hanya pasangan alias komunitas, apalagi memusingkan pelakunya sendiri.
Tahun 2023, The US Surgeon General’s Advisory mengeluarkan kajian nan mencemaskan mengenai indikasi loneliness di negeri itu. Mereka menyebut kehampaan sebagai epidemi. Menurut WHO, satu dari enam orang di muka bumi mengalami kesepian. Survei Gallup mencatat 24% orang nan berumur 15 tahun alias lebih tua mengalami derita kesepian. Masalah ini memburuk di negara-negara berpenghasilan rendah. Menurut survei itu, separuh dari orang dewasa di Brazil mengalami alias pernah merasa kesepian. Turki 46%, India 43%.
Kehampaan meningkatkan kematian prematur hingga 65%, apalagi lebih jelek dari mengepul 15 batang rokok per hari. Kehampaan menurut beragam analisa nan ada dapat diatasi dengan membangun jaringan sosial. Ketika mengalami deru debu kehidupan, hubungan sosial membikin angan kita untuk memperkuat meningkat hingga 50%.
Kehampaan menjadi pandemi di kota-kota tidak semata-mata lantaran lenyapnya jaringan sosial pendukung. Lebih dari itu, hilangnya rumah alami (bumi nan asri) juga ikut merapuhkan pertahanan diri seseorang. Sebab, hutan, bunga, sungai nan jernih, dan bentang alam nan asri mempunyai keahlian alamiah untuk membersihkan debu dan kotoran nan melilit pikiran kita. Alam nan bagus adalah rumah nan damai, tempat stress dikuburkan, tanpa kudu kuatir bakal menjadi bahan gosipan tetangga. Alam juga memberi pengaruh charging positif pada emosi tenang nan memulihkan tekanan mental. Bahkan dalam banyak studi dapat menyehatkan seseorang melalui suatu proses nan disebut ekoterapi.
Menurut saya, solastalgia bukan semata-mata dipicu oleh pengalaman-pengalaman sensorik dari luar. Perasaan terasing juga berkarakter spiritual. Dalam pandangan agama-agama samawi, manusia pernah mengalami taman Eden nan indah. Eden dimana segalanya ada.
Suatu negeri ideal nan diabstrasikan nyaris nyata dalam pikiran nyaris semua orang beragama. Para filsuf nan berdiri di alam buahpikiran seperti Plato meyakini bahwa kehidupan di bumi hanya cermin tak sempurna dari rekaman pengalaman alam surgawi nan sempurna itu. Tetapi manusia memperjuangkan kehadiran buahpikiran itu secara partikular untuk membumi dalam alam sekitar nan terhubung dan mendukung manusia sehari-hari.
Meskipun tidak sepenuhnya mewakili keelokan nan ideal dari Firdaus, manusia merawat khayalan tersebut melalui hubungan nan memberikan kenyamanan dari alam. Ini sangat kuat pada suku-suku original alias bumi pertanian ketika intervensi industri belum begitu dominan. Relasi dengan alam tetap dijiwai oleh relasi spiritual. Sehingga, wajah Eden tetap ditemukan di sana.
Manakala alam nan terhubung tersebut dihancurkan, tidak hanya ikatan sensorik nan lenyap, tetapi satu-satunya gambaran nyata nan dapat diraih dari khayalan Eden ikut musnah. Kehancuran ekologis tidak hanya membikin manusia kehilangan tanah dan rumah tetapi juga mencerabutnya dari ingatan bakal asal muasal manusia dari negeri Eden. Karena itu, solastalgia adalah emosi manusia tercerabut dari memori bakal firdaus dan nostalgia itu mendorongnya untuk memberontak agar ingatannya itu dipulihkan.
Perasaan tercerabut nan paling mendasar adalah ketercerabutan pengalaman jiwa dari khayalan ideal tentang alam. Pengalaman ini tidak dapat diukur, sehingga tidak dapat pula ditelisik karena musabah materialnya. Pengalaman itu hanya bisa dijelaskan dari emosi itu sendiri. Karena itu, kita bisa memahami pengalaman masyarakat original nan merasa tercerabut dari tanah mereka akibat perubahan bentang alam nan menjungkalkan hutan, sungai, danau, apalagi rumah mereka. Itu semua membikin mereka tergusur tidak hanya secara fisik, tetapi spiritualitas mereka pada “Eden” jenis mereka ikut lenyap.
Solastalgia, pada titik tertinggi adalah solaspiritual ialah kesenyapan spiritual akibat kerusakan alam. Kesepian ini semestinya mengundang kita kembali pada sang Pencipta bukan untuk meratap dan berdoa, tetapi bertindak nyata. Dalam perihal ini semua kepercayaan meyakini bahwa manusia bukan sebagai penghancur tetapi perawat dan penjaga bumi.
Dalam pengertian itu maka, pembangunan modern kudu dikonstruksikan kembali agar sungguh menempatkan manusia sebagai perawat dan penjaga. Dalam tindakan nyata, agama-agama semestinya menjadi pelopor pemulihan ekologis, bukan sebaliknya mengeruk daratan, menggasak lautan dan menambah derita solastalgia nan diproyeksikan bakal bertambah di hari esok.

.png) 2 minggu yang lalu
2 minggu yang lalu




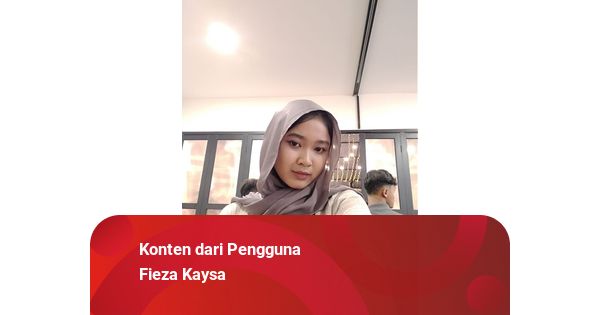

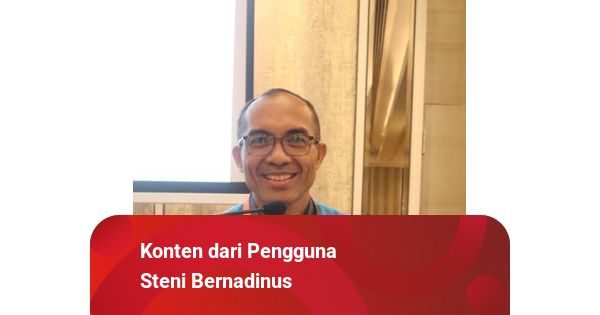

 English (US) ·
English (US) ·  Indonesian (ID) ·
Indonesian (ID) ·